Sahur Di Aceh Pada Masa DOM dan Huzun-nya Orhan Pamuk
 |
| source: kippas |
Dulu, sekira terhitung belasan tahun lalu, pernah kita merasakan suatu sahur yang payah. Sahur-sahur yang latah oleh sebab letus peluru. Kita menjalaninya dengan khusyu' sambil tak pernah lepas merapal do'a agar selamat hidup di dunia hingga mati dengan cara yang sewajar-wajarnya. Bukan mati di ujung moncong senjata. Bukan mati karena degup jantung berlebihan seusai disepak tulang kering dengan sepatu lars tentara. Sahur-sahur seperti itu adalah sahur yang tak pernah diterka oleh olah pikir siapa pun. Tak pernah juga diharapkan oleh benak seseorang yang benar-benar manusia.
Dulu, sahur-sahur begini kita lewatkan dengan senyap. Ayah atau abang-abang pulang ketika sirene sahur dikumandangkan dengan lirih melalui corong mikrophone meunasah dari tugas jaga malam yang melelahkan. Sambil sesekali (di kampung dekat gunung banyak kali) ketika di tikungan terakhir dekat rumah, para orangtua-orangtua selalu berpapasan dengan bergoyangnya dan gemerisik ilalang, bak laya, bak lipah, dan lain sebagainya. Itu bukan goyang dan gemerisik karena ada angin atau sekawanan babi singgah berumah semalaman di sana. Tidak. Itu adalah gemerisik sekawanan tentara yang tingkat kecurigaannya hanya bisa digambarkan dengan kata naudzubillah, mengendap semalaman tanpa tidur, berkawan nyamuk dan rentan mengamuk. Dan para orangtua-orangtua menganggap hal itu sudah biasa sambil memendam perasaan takut yang amat sangat.
Dulu, sahur-sahur di kampung adalah sahur yang dihabiskan dalam diam. Bahkan untuk sekadar mengolok-olok (hingga berakhir pada pertengkaran kecil) dengan adik kecil yang setiap dibangunkan untuk makan sahur selalu menangis, kami hanya bisa melakukannya dengan bisik-bisik agar suara tidak semena-mena keluar rumah. Bayangkan, lelucon apakah yang bisa menggambarkan pertengkaran di meja makan yang harusnya meriah hanya dilakukan dengan berbisik-bisik saja?
Kini, kami sudah tak bisa lagi menggambarkan saat-saat murung itu walau sekadar menguatkan ingatan bahwa 'kebahagiaan' sekarang didapat dari sebuah proses pahit. Sebuah proses yang menggerus banyak nyawa, yang ketika kami dewasa kami lupa tentang semuanya. Tapi adakalanya juga kami dikejutkan oleh mimpi tentang perihal-perihal buruk dulu itu. Dan keesokannya kami menganggap itu sekadar mimpi buruk yang dibawa angin buruk dari sebuah kampung terkutuk.
Kini, membangunkan ingatan itu kembali, bagi sebagian orang yang telah hilang ingatan adalah sama halnya seperti membangunkan geugasi (baca: monster) yang tidak hanya menurunkan selera makan, tapi membuat mereka tiba-tiba sakit gigi. Sementara bagi kami yang belum ingin hilang ingatan begitu saja mengadopsi istilah Orhan Pamuk dalam memoarnya berjudul Istanbul sebagai representasi bahwa ada banyak pelajaran dari pengalaman buruk masa lalu. Untuk merepresentasikan situasi-situasi sahur zaman dulu yang murungnya minta ampun, kami mengutip istilah huzun dari seorang Pamuk.
Seperti ditulis Pamuk, huzun dalam bahasa Turki berarti kemurungan. Yaitu adopsi dari akar kata bahasa Arab: huzn yang juga memiliki makna sama. Nabi Muhammad menyebut tahun ketika beliau kehilangan istrinya, Khadijah, dan pamannya, Abu Thalib, sebagai "sanatul huzn" atau tahun kemurungan; ini menegaskan bahwa kata itu memiliki arti perasaan kehilangan yang amat spiritual.* Mengutip Al-Kindi, Pamuk lebih lanjut menulis, bahwa pada tahap selanjutnya, huzun diasosiasikan tidak hanya dengan kehilangan atau kematian seseorang yang kita cintai, tetapi juga dengan penderitaan-penderitaan spiritual lain seperti kemarahan, cinta, kebencian, dan ketakutan yang tak berdasar.**
Maka mengenang pengalaman melewatkan sahur (sebenarnya tidak hanya sahur saja) di Aceh pada masa DOM dengan keterkaitan huzun-nya Orhan Pamuk dalam memoarnya itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana menderitanya kami melewati masa-masa penuh takut yang laten. Ketakutan yang tak bisa dijabarkan oleh bergeraknya pita suara tapi bisa dengan mudah terbaca dari gurat-gurat mimik muka.
Untuk kemurungan pada saat sahur-sahur seperti itu, iya, kami hanya membicarakannya dengan mimik muka. Membicarakannya dengan kebisuan yang sungguh-sungguh durjana. Bagaimana kami bisa menangkap ketakutan yang menyandrung ayah dari kepucatan wajahnya ketika pulang dari tugas jaga malam. Itu sudah cukup membuat kami seisi rumah mengerti, mungkin ayah baru kena push-up ratusan kali. Atau boleh jadi, ketika jaga malam tadi jidat ayah tersentuh (disentuhi) dinginnya moncong SS-1 atau M-16 oleh musabab yang jika ditinjau kembali tak pernah benar-benar bisa dijadikan sebab.
Bagaimana kami menangkap ketakutan ibu ketika menyiapkan makanan sahur di dapur, tanpa sengaja membuang air sisa cuci piring melalui jendela belakang yang sebelum air itu jatuh menerpa tanah sudah duluan disambut dengan sebuah bentakan maha lantang dari luar rumah: "Bangsat. Keluar semua!"
Kami menyaksikan ibu pucat tiba-tiba. Tak bisa lagi berbuat apa-apa, walau kuah masam keu-eueng (kuah asam pedas) sudah mendidih, berbuih-buih di atas tungku. Barangkali, keadaan seperti itu adalah maha huzun lain yang untuk menangkap detail-detail ketakutan atau molekul-molekul kemurungan dari sebuah sahur di musim perang terkutuk, kami hanya bisa menjabarkannya dengan linang air mata. Linang air mata yang membanjir di dua kelopak mata, tapi enggan meluap keluar untuk membentuk anak sungai di dua belah pipi kami. Ibu juga mengalami hal yang sama.
Sementara adik kecil, meraung keras sambil berucap, "Ayah ho? Ayah ho? (Ayah mana? Ayah mana?). Sementara di luar, teriakan makin membahana saja, "Keluar. Keluar semua. Cepat keluar. Atau kami bakar semua!"[]
Klebang - Emperom, medio 2019-2014.
__________________
Keterangan:
* Orhan Pamuk, Istanbul: Kenangan Sebuah Kota, terj. Rahmanuti Astuti, Jakarta: Serambi, 2009, hal. 128.
** Ibid, hal. 130-131.
Tulisan ini adalah untuk mengenang seorang teman ngopi di Cek Wan Ulee Kareng dan teman main bola beda kampus di lapangan Tugu Darussalam, yang sudah hilang kontak sejak tahun 2004 sebab tsunami. Yang dari mulutnyalah keluar cerita dibakarnya rumah keluarganya pada sebuah sahur bulan puasa tahun 1997 ("Itu ketika saya masih kelas dua SMP," katanya waktu itu sambil menahan air matanya agar tak tumpah ketika bercerita), di sebuah kampung pedalaman Aceh Timur yang nama kampung dan kecamatannya benar-benar aku lupa. Aku ingat, ia bercerita haba maha duka ini pada sebuah sore di Warkop Cek Wan Ulee Kareng, sekitar
tanggal 20-an ke atas bulan April 2004. Beberapa hari setelah ia
mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 padaku. Untuk Hamidi Rusli: "Allahummagh-firlahu warhamhu, wa 'aafihi wa'fuanhu, wa-akrim nuzuulahu, ..." Sejatinya, tulisan ini sudah mulai saya tulis sejak tahun 2009 (berisi dua paragraf terakhir juga keterangan), dan baru tadi saya temukan kembali ketika membongkar file-file lama.
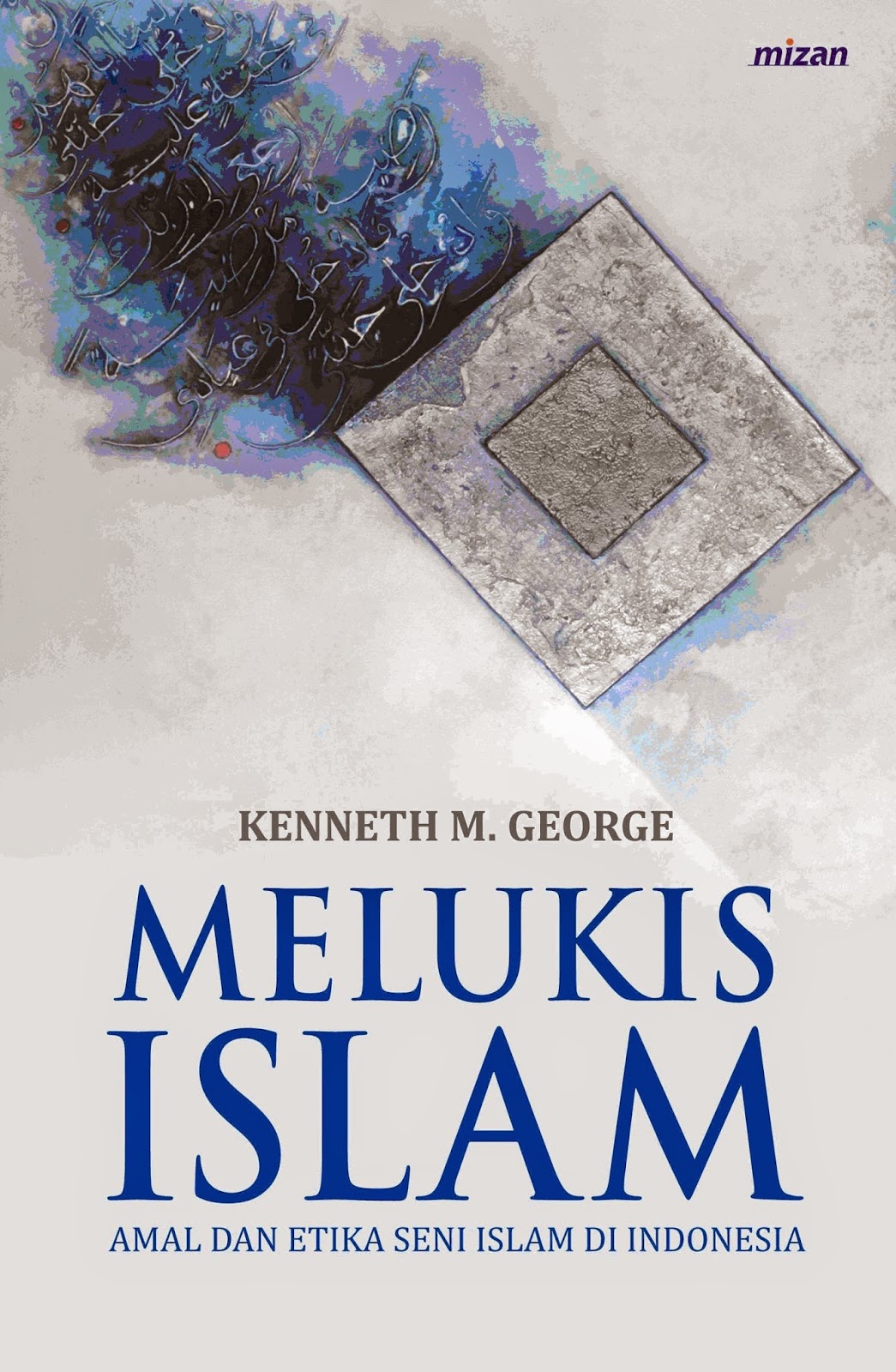
Comments
Post a Comment