Kiat-kiat Mendirikan Bioskop Di Banda Aceh
Bagi orang-orang muda yang punya akal budi serta pikiran visioner,
sanggahan begitu rupa tentu saja tidak jadi soal. Sebab, kalau itu jadi soal, sudah
barang tentu lebih baik seuk keudeh beu jioh (geser sana yang jauh) dari
komunal muda intelektual. Kenapa begitu? Ya, bagi yang punya daya intelegensi
tinggi, barangkali tahu sebabnya kenapa.
Atas nama pendidikan bioskop itu penting. Bioskop adalah salah satu media
alternatif bagi pembelajaran. Sebab yang namanya belajar, ia tidak hanya
berkisar dengan membaca menulis saja. Menonton film-film edukatif juga.
Barangkali, orang-orang di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh sangat-sangat
mengerti soalan ini.
Namun, kata bioskop sudah kadung dimaknai negatif oleh orang-orang tua yang
punya hak di jawatan agama. Entah mimpi buruk apa, bioskop sudah dianggap jadi
semacam ‘rumah maksiat’ bagi kaula muda. Menghadapi kenyataan seperti ini, saling
membesar-besarkan pita suara adalah lucu. Oleh sebab itu, kerja-kerja seperti mengklasifikasikan jenis bioskop yang
bagaimana yang sesuai untuk pendidikan di Banda Aceh adalah penting.
Maka kiat-kiat seperti menginisiasi persepsi klasifikasi bioskop yang
bagaimana, seperti yang telah dilakukan pekan silam oleh anak-anak muda lintas komunitas di Banda Aceh (saya turut menyesal sebab tak sempat hadir karena ada halangan pekerjaan) adalah benar adanya. Hanya
saja, inisiasi lintas komunitas, seperti komunitas perfilman, dan lain
sebagainya di Banda Aceh hendaknya mampu menghasilkan satu persepsi konkrit
tentang jenis bioskop yang ingin diminta ada di tengah-tengah kita. Sebab,
seperti yang saya dengar-dengar, di dunia ini, ada dua jenis bioskop yang tegak berdiri di
hampir seantero belahan dunia mana pun. Kecuali belahan dunia Provinsi Aceh,
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama sekali sudah tidak ada lagi.
Satu bioskop berjenis komersil. Satunya lagi sebaliknya. Jika yang komersil
menayangkan film-film perusahaan bisnis perfilman seperti film produk Hollywood,
Bollywood, Koreawood, juga RaamPunjabiwood (untuk dua perusahaan terakhir entah
benar-benar ada), bioskop non komersil menayangkan produk-produk film
dokumenter yang sarat unsur-unsur pendidikan di dalamnya. Ambil contoh, seperti
film Jalan Pedang karya Dandhy Laksono beberapa pekan sebelum bulan puasa
kemarin di Aula Lantai IV Balai Kota Banda Aceh adalah film yang cukup
inspiratif dan sangat-sangat layak ditonton oleh semua orang Aceh.
Mengingat di Banda Aceh sendiri, pelaku-pelaku film dokumenter yang sudah go
nasional semakin menjamur saja, tempat penayangan hasil karya mereka adalah
penting.
Mengacu pada terbenturnya anggapan bioskop dalam stigma para orang tua
kita, ada baiknya untuk jenis bioskop edukatif yang kita harapkan itu diberi
nama konkrit dengan tidak memakai kata bioskop sama sekali. Misalnya, dikasih
nama Taman Edukasi Visual Banda Aceh, atau apalah nama-nama lainnya yang lebih
pendek lagi katanya. Oya, kalau dikasih nama Tong Setan, lebih baik jangan.
Tentang yang tersebut di atas, saya ingat cerita Apa Kaoy atau M. Yusuf
Bombang, seniman gaek Aceh, sewaktu ngopi di kedainya di bilangan Lampaseh Kota bersama
Zulfan Amroe dan Muhajir Abdul Aziz beberapa bulan lalu. Kalau belum bosan
membaca ini tulisan, ceritanya seperti berikut ini:
“Suatu hari, kami bersama beberapa musisi di Banda Aceh ada acara manggung
di sebuah gampong di Aceh, yang namanya tak perlu saya sebutkan sama kalian.
Waktu itu, sebagaimana disuruh oleh panitia, kami manggung untuk mengisi acara
pantun dan musik dalam rangka kampanye damai paska konflik. Tengah menyiapkan
peralatan manggung, yaitu alat-alat musik seperti rapai, gitar, seurunee kalee,
seorang tokoh masyarakat di sana memanggil saya.
“Acara apa ini? Acara band ya? Tidak boleh kalau ada acara band di sini.
Tidak baik. Bubarkan saja. Kami tidak sudi ada band-band-an di kampung ini,”
tanyanya berapi-api.
Saya katakan pada tokoh yang dari pakaiannya bisa ditebak kalau ia orang
berpengaruh di tengah masyarakat setempat, itu terlihat dari pecinya yang
lusuh, tidak ada acara band nanti. “Kami hanya main hikayat saja. Cuma agar
hikayat enak didengar orang, di atas panggung nanti diringi rapa’i sedikit, tiup
seureunee kalee sedikit, dan suara gitar sedikit. Coba lihat mana ada band di
panggung. Tidak ada alat musik. Yang ada, ya itu, rapa’i, seureunee kalee, dan gitar.
Jangankan main band, main musik saja kami tidak. Boleh lihat sendiri nanti,” kata
saya pada tokoh masyarakat itu.
“Oh. Saya pikir ada band. Ada main musik. Kalau hikayat saya suka. Kalau
begitu baiklah. Bawakan hikayat yang bagus nanti. Saya ingin menonton juga,”
jawabnya sambil tersenyum ramah sambil cepat-cepat berlalu.
“Jadi begitulah. Di Aceh, di kampung yang tak ingin saya sebutkan nama itu,
main musik tidak boleh. Kalau pukul rapa’i, tiup seureunee kalee, dan petik
gitar, itu tak apa. Asal jangan main musik. Jadi begitulah orang-orang kita.
Nyatanya, ada beberapa lagu yang kami mainkan pada malam baik itu, dan si tokoh
yang menyanggah saya sebelumnya juga bertepuk tangan riuh di penghujung acara,”
tutup cerita Apa Kaoy kepada kami. Waktu itu, kami bertiga serempak bersuara, “Hahahahahaha...!”
Kembali ke soalan bioskop untuk Banda Aceh, kiat-kiat seperti saya sebutkan
di atas tentu saja sudah dipikirkan oleh teman-teman yang lainnya juga. Tinggal
bagaimana meneguhkan persepsi jenis bioskop bagaimana yang dimaui, yang
kemudian kesepakatan itu tersusun baik dalam sebuah draft tertulis. Di mana
dalam draft tersebut berisi hal-hal teknis dan non teknis berkenaan dengannya. Misalnya
hal teknis berupa pemisahan bangku tonton lelaki dan perempuan seperti halnya
tempat wudhu’ di masjid-masjid atau meunasah-meunasah.
Sementara untuk hal-hal lain, dengan melibatkan pelbagai komunitas,
khususnya komunitas perfilman di Banda Aceh serta Dewan Kesenian Banda Aceh
(DKB) tentu akan ada kejelasan yang lebih lagi, di mana hajat ruang ekspresi
anak-anak muda di Banda Aceh dapat terpenuhi nantinya. Wassalamu![]
______________
Nb. Terjemahan basa Aceh di atas. *"Sedang kita adu Balam, kau lempar Kucing dalam gelanggang. Mengganggu saja kerjanya!"
Ilustrasi foto adalah pemaksaan kehendak pemilik blog belaka. Jangan pikir itu gambar bekas bangunan bioskop di Banda Aceh. Tidak. Itu gambar bekas bangunan rumah setelah diterjang tsunami, yang sampai sekarang ini masih berdiri kokoh di Gampong Lamdingin sana.

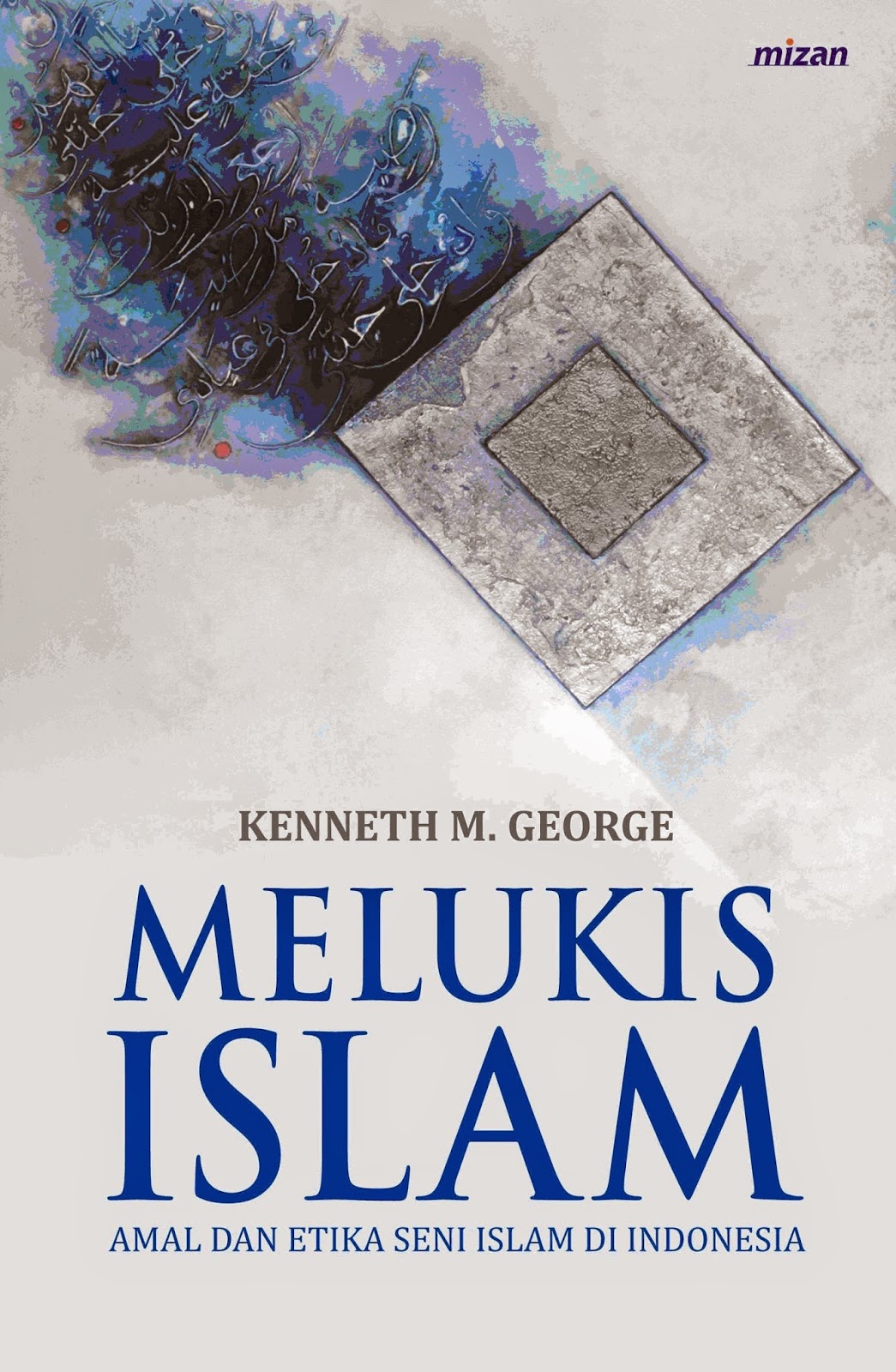
Comments
Post a Comment