Tak Ingin Membati Buta
 |
| doc. idrus bin harun |
Kiranya ketika melangkah, kita butuh penunjuk arah. Sebab kita masih buta. Kita memang buta. Ya, hakikatnya kita benar-benar buta, walau mata terbelalak, terpelotot lebar terbuka. Kita mesti mengakui banyak hal tentang kebutaan ini. Mungkin kita pernah membaca kalimat Seno Gumira Aji Darma dalam Kisah Mata. Sebutnya, "... dunia ini penuh dengan keajaiban karena hal-hal yang tidak masuk akal masih terus berlangsung. Seorang fotografer ingin membagi duka dunia di balik hal-hal yang kasat mata. ..., para fotografer membagi pandangan, tetapi yang memandang foto ternyata buta meskipun mempunyai mata." Kita tahu yang dimaksudkan Seno dalam kutipannya tak lain adalah sinyal untuk menerangkan bahwa kebutaan manusia pada dasarnya tidak melulu berhubungan dengan indera melihat saja. Tapi ia menerangkan dengan halus, bahwa, meskipun seseorang punya mata, tetapi hakikatnya dia adalah seorang buta. Kenapa demikian? Boleh jadi, hal keadaan demikian disebutkan karena banyak di antara kita sudah tak tahu memfungsikan mata dengan baik dan benar. Dan mata yang dimaksudkan itu, boleh jadi juga adalah mata yang menyemat dalam hati. Mata hati. Bukan mata kepala kita sendiri. Maka adalah kita yang belum punya mata hati, ketika melangkah, ketika menembus arah, kita memerlukan alat semacam kompas, atau penunjuk arah. Kompas mata hati adalah ilmu yang berpadu dengan akal pikiran. Dengannya kita tak sesat di jalan. Dengannya kita tak bakal hilang lembar-lembar ingatan.
Sesat adalah pertanda bahwa kita keras kepala dan merasa tak penting akan kompas atau penunjuk arah sejenisnya. Jalan penuh jalur, penuh simpang, juga penuh aral melintang kita lalui saja tanpa banyak perhitungan. Hasilnya? Dapat ditebak. Di kelokan yang kita tak tahu di mana, di simpangan yang tak ada rambu-rambu petunjuk, atau di jalan lurus yang dari kejauhan menawarkan fatamorgana, suatu bahaya besar menanti kita. Hasilnya? Jangan ditanya. Kita terpelanting ke belakang atau malah akal waras, jabatan, harta, dan lain sebagainya yang sedang kita punya segera menghilang. Karenanya, tak ada banyak alasan selain setuju bahwa penunjuk arah adalah sesuatu yang penting bagi kita. Pun kita tak pernah ingin berjalan atau mengembara. Kita tetap butuh penunjuk arah yang menuntun setiap gerak dalam diri kita. Mungkin kaki tak pernah ingin bergerak, tak selalu ingin melangkah; tapi hati, pikiran, darah, ingatan, air, udara, yang ada dalam diri kita tentu tak sama seperti sang kaki. Kesemua dari mereka, semua yang ada dalam tubuh kita, tetap ingin bergerak dengan leluasa. Bergerak atas dasar dan dengan cara sifat alamiahnya.
Pun begitu, ada juga salah satu dari kita semua, pernah ingin benar-benar buta. Suatu waktu yang tak menentu, ia menyebut; "Ajarkan aku menjadi buta, agar aku lupa dengan warna. Segalanya serupa, dalam surga yang aku sebut fana." [Adi Wiwid, an Architect]. Pada taraf keinginan seperti ini, kita tak dapat mengartikulasikannya dengan semena-mena. Sebab, ketika seseorang ingin menjadi buta, ia sudah cukup punya alasan dengan pilihannya. Dan kita pun tak bisa mencegahnya. Hanya saja, walaupun ia punya alasan terbaik dalam menerangkan pilihannya, kita patut curiga pula. Curiga dalam arti bukan untuk berburuk sangka. Curiga dalam taraf mempertanyakan efek dari pilihannya saja. Tidakkah buta dapat membuatnya linglung bingung? Atau, bukankah ketika dilanda buta, seseorang akan dibalut hitam legam? Apa-apa menjadi pekat. Segala yang ada sekonyong-konyong hilang secara mata mengkasat. Bukankah begitu efek yang ditimbulkan buta? Atau, kau sudah benar-benar punya mata hati yang sempurna? Atau, benarkah mata hati yang kau punya sudah benar-benar sempurna? Di sini, kita tidak bisa benar-benar percaya, jika seseorang ini berkilah bahwa ia sudah punya mata hati yang cerah, bercahaya mencercah, gilang gemilang dalam menembus segala penglihatan. Barangkali ia mempunyai penglihatan lain, selain mata kepala dan mata hati. Barangkali, dia ingin mengandalkan mata rasionalitasnya belaka.
Maka darinya, kita sangat membutuhkan petunjuk arah untuk memaknainya. Kita membutuhkan peralatan penunjuk arah untuk membuat cerah mata hati dan mata kepala yang ada. Mungkin ilmu, mungkin petunjuk guru, atau mungkin juga pengalaman hidup sehari-hari yang berpadu di dalamnya antara ilmu dan petunjuk guru. Hingga di akhir, kita tak sama setuju jika seseorang yang datang dari jauh, datang dan mengeluh; "Ajarkan aku menjadi buta, agar aku lupa dengan warna. Segalanya serupa, dalam surga yang aku sebut fana." Benarkah surga itu fana? Kita rasa tidak demikian adanya.
Dec. 2011, Bivak Emperom.
qoutes source: http://www.goodreads.com/quotes/tag/buta
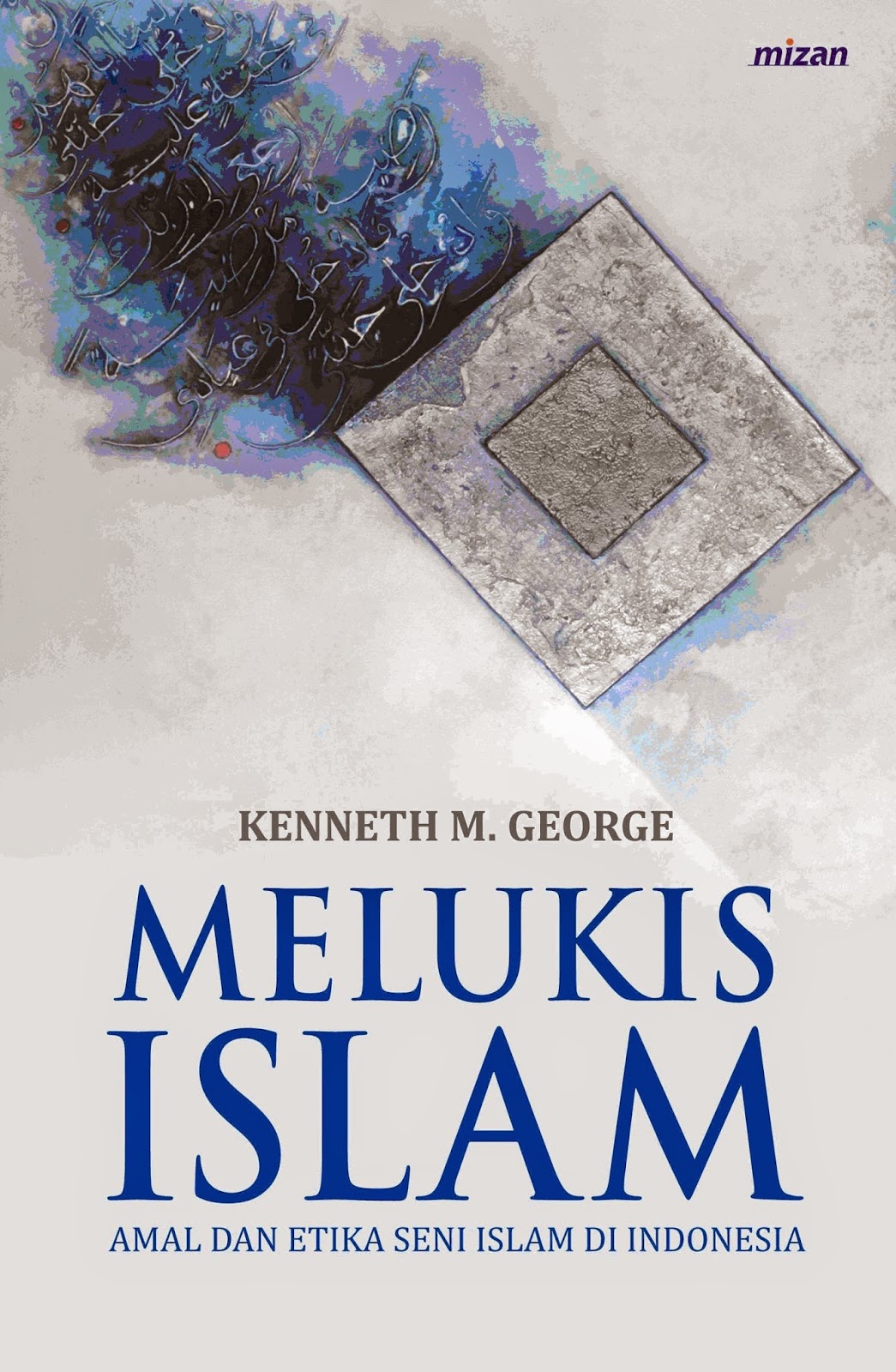
ja.membabi buta,kan?
ReplyDeleteYa, marilah kita melihat semua simpang itu, Ja. Hai, neusaweulah sigoe-goe, tabeurakah sajan di Komunikasi Sastra nyan.
ReplyDelete