Catatan Akhir Kampus
Maka di kampuslah kau bisa menimbang-nimbang isi kepala yang kau punya. Argumen-argumen yang kau paparkan kerap pupus oleh aduan argumen lain dari seorang teman sekelas dan juga dosen. Di kampus pulalah kau bisa menyejajarkan bahu dengan orang-orang (banyaknya merasa diri) berwawasan luas, banyak baca buku, paham pelbagai teori, untuk kemudian kau keluar dari ruang kuliah dalam keadaan was-was. Kau mendapati diri antara mengerti atau tidak; bahwa teori-teori yang kau pahami selama ini tidak sesuai dengan kerangka kurikulum misalnya. Bahwa kurikulum telah cukup berhasil membantu teman-teman sekelas untuk mengungkungkan diri dalam teori-teori tinggi tapi tak pernah bisa membumi ketika kau terapkan di meja-meja kedai kopi.
Sabtu, 20 September 2014, pagi-pagi sekali aku bangun, mandi, pakai shampo, sabun, dan gosok gigi. Kemudian dengan gegas berpakaian rapi. Ada kelas di kampus yang mesti kuhadiri setelah dua tahun sebelumnya kutinggalkan begitu saja. Kupacu sepeda motor dari Emperom menuju Darussalam dengan gesa. Untuk kelas pertama, aku tak ingin terlambat. 17 menit, 6 persimpangan berlampu merah, kulalui dengan selamat tanpa kurang suatu apa, tanpa keduluan dosen memasuki ruang kuliah.
Sesampai di kampus, dua tahun tak menginjakkan kaki di sini, ada nuansa lain yang harus kuhadapi. Ruang kuliah telah banyak bertukar tempat. Teman-teman lama satu pun tak tampak batang hidungnya lagi. Kebanyakan sudah lulus satu-dua tahun belakangan, sisanya lagi 'melarikan diri'. Ada yang sudah duluan berumah tangga, ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Aku mesti beradaptasi lagi. Sama seperti bagaimana aku beradaptasi pada semester pertama tiga tahun lalu. Mesti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman baru, seperti; dulunya kuliah di mana? Jurusan apa? Dan sekarang bekerja di mana? Aku bersyukur, pohon-pohon angsana yang tumbuh teduh di halaman kampus tak pernah mengeluarkan pertanyaan yang sama atau ikut-ikutan menambah pertanyaan; sudah nikah belum? Tapi syukurnya lagi, adaptasi begini rupa berlangsung singkat. Dosen masuk, hampir semuanya sibuk dengan diktat.
Di kelas, ada 11 orang teman baru duduk dalam formasi huruf U menghadap seorang dosen, yang sedari pertama masuk: ucap salam, sapa sana sini sebentar, duduk, meminta tisu dari seorang mahasiswi, lantas sibuk membersihkan layar dua smartphone dan seperangkat laptopnya. Dalam ruangan ini, aku seperti menemukan diri sedang berbaur dengan orang-orang yang serba khusyu'. Kelas terasa dingin. Sedingin udara dalam ruangan yang memakai mesin pendingin dengan suhu 22 derajat celcius. Sangat tidak nyaman untukku yang sudah sejak dulu menderita sinusitis. Tapi teman-teman lain tampak begitu nyaman, kecuali salah satu di antaranya yang tak melepas jaket berlogo klub bola Real Madrid sejak masuk tadi. Kupikir, ia berasal dari daerah pesisir utara dan tak terbiasa dengan udara dingin di ketinggian pegunungan seperti di Gayo, Pameue, atau Geumpang, yang pagi-pagi begini rupa berpindah ke sini.
Kelas pada jam pertama sekarang adalah kelas mata kuliah Ilmu Tasawuf. Dosen telah memulai bicara setelah kesibukannya bebersih layar gadgetnya selesai. Aku menyimak. Yang lainnya juga. Suhu dalam ruangan tambah dingin. Tapi kemudian berimbang dengan suhu pembicaraan bertopik pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Itu mengemuka setelah dosen menguraikan pandangannya tentang hukum cambuk terhadap beberapa orang tersangka pelaku maisir (judi) di Masjid Taman Makam Pahlawan, Gampong Ateuk Banda Aceh kemarin.
Ia menyayangkan pemberlakuan syariat Islam di sini seperti hanya berlaku untuk orang-orang kecil yang kedapatan bersalah belaka. Selalu yang kena hukum cambuk orang-orang kelas menengah ke bawah, sementara para koruptor misalnya, yang jelas-jelas kedapatan mencuri uang pemerintah, uang rakyat, tak pernah tersentuh oleh hukum syariat. Ini lucu. Menurutnya begitu. Lantas pembicaraan beralih pada tema tasawuf, sesuai dengan mata kuliah yang diasuhnya.
Seseorang memilih jalan sufi, kata dosen, untuknya ia disebut sebagai seorang calon sufi. Memilih jalan ini, paparnya lagi, haruslah terlebih dahulu mengekalkan tobatnya dengan sungguh-sungguh atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama ini. Baru kemudian si calon sufi mengekalkan ibadahnya baik yang wajib, mau pun yang sunat, dengan sungguh-sungguh pula. Sungguh-sungguh di sini, menurutnya adalah dalam artian selalu dijalankan dengan penuh ikhlas, tidak riya, wara', dan dalam prosesnya tersebut si calon sufi tidak serta merta membumbung tinggi ke awan, tidak lagi menginjak bumi. Maksudnya, ketika si calon sufi berproses untuk kesufiannya, ia tak serta merta meninggalkan tugasnya sebagai makhluk sosial. Tidak meninggalkan hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga misalnya, kepala sekolah, teungku, guru, dosen, dan bahkan tidak serta merta melupakan tanggung jawab atas dirinya sendiri.
Ini bagian penting menurutku. Bahwa, mengutip tulisan kecil seorang 'teman dekat', "Ga harus terbang ke awan kan untuk melihat langit? Kita masih bisa melihatnya dengan tetap menapakkan kaki di tanah." bersambung ...
Sabtu, 20 September 2014, pagi-pagi sekali aku bangun, mandi, pakai shampo, sabun, dan gosok gigi. Kemudian dengan gegas berpakaian rapi. Ada kelas di kampus yang mesti kuhadiri setelah dua tahun sebelumnya kutinggalkan begitu saja. Kupacu sepeda motor dari Emperom menuju Darussalam dengan gesa. Untuk kelas pertama, aku tak ingin terlambat. 17 menit, 6 persimpangan berlampu merah, kulalui dengan selamat tanpa kurang suatu apa, tanpa keduluan dosen memasuki ruang kuliah.
Sesampai di kampus, dua tahun tak menginjakkan kaki di sini, ada nuansa lain yang harus kuhadapi. Ruang kuliah telah banyak bertukar tempat. Teman-teman lama satu pun tak tampak batang hidungnya lagi. Kebanyakan sudah lulus satu-dua tahun belakangan, sisanya lagi 'melarikan diri'. Ada yang sudah duluan berumah tangga, ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Aku mesti beradaptasi lagi. Sama seperti bagaimana aku beradaptasi pada semester pertama tiga tahun lalu. Mesti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman baru, seperti; dulunya kuliah di mana? Jurusan apa? Dan sekarang bekerja di mana? Aku bersyukur, pohon-pohon angsana yang tumbuh teduh di halaman kampus tak pernah mengeluarkan pertanyaan yang sama atau ikut-ikutan menambah pertanyaan; sudah nikah belum? Tapi syukurnya lagi, adaptasi begini rupa berlangsung singkat. Dosen masuk, hampir semuanya sibuk dengan diktat.
Di kelas, ada 11 orang teman baru duduk dalam formasi huruf U menghadap seorang dosen, yang sedari pertama masuk: ucap salam, sapa sana sini sebentar, duduk, meminta tisu dari seorang mahasiswi, lantas sibuk membersihkan layar dua smartphone dan seperangkat laptopnya. Dalam ruangan ini, aku seperti menemukan diri sedang berbaur dengan orang-orang yang serba khusyu'. Kelas terasa dingin. Sedingin udara dalam ruangan yang memakai mesin pendingin dengan suhu 22 derajat celcius. Sangat tidak nyaman untukku yang sudah sejak dulu menderita sinusitis. Tapi teman-teman lain tampak begitu nyaman, kecuali salah satu di antaranya yang tak melepas jaket berlogo klub bola Real Madrid sejak masuk tadi. Kupikir, ia berasal dari daerah pesisir utara dan tak terbiasa dengan udara dingin di ketinggian pegunungan seperti di Gayo, Pameue, atau Geumpang, yang pagi-pagi begini rupa berpindah ke sini.
Kelas pada jam pertama sekarang adalah kelas mata kuliah Ilmu Tasawuf. Dosen telah memulai bicara setelah kesibukannya bebersih layar gadgetnya selesai. Aku menyimak. Yang lainnya juga. Suhu dalam ruangan tambah dingin. Tapi kemudian berimbang dengan suhu pembicaraan bertopik pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Itu mengemuka setelah dosen menguraikan pandangannya tentang hukum cambuk terhadap beberapa orang tersangka pelaku maisir (judi) di Masjid Taman Makam Pahlawan, Gampong Ateuk Banda Aceh kemarin.
Ia menyayangkan pemberlakuan syariat Islam di sini seperti hanya berlaku untuk orang-orang kecil yang kedapatan bersalah belaka. Selalu yang kena hukum cambuk orang-orang kelas menengah ke bawah, sementara para koruptor misalnya, yang jelas-jelas kedapatan mencuri uang pemerintah, uang rakyat, tak pernah tersentuh oleh hukum syariat. Ini lucu. Menurutnya begitu. Lantas pembicaraan beralih pada tema tasawuf, sesuai dengan mata kuliah yang diasuhnya.
Seseorang memilih jalan sufi, kata dosen, untuknya ia disebut sebagai seorang calon sufi. Memilih jalan ini, paparnya lagi, haruslah terlebih dahulu mengekalkan tobatnya dengan sungguh-sungguh atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama ini. Baru kemudian si calon sufi mengekalkan ibadahnya baik yang wajib, mau pun yang sunat, dengan sungguh-sungguh pula. Sungguh-sungguh di sini, menurutnya adalah dalam artian selalu dijalankan dengan penuh ikhlas, tidak riya, wara', dan dalam prosesnya tersebut si calon sufi tidak serta merta membumbung tinggi ke awan, tidak lagi menginjak bumi. Maksudnya, ketika si calon sufi berproses untuk kesufiannya, ia tak serta merta meninggalkan tugasnya sebagai makhluk sosial. Tidak meninggalkan hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga misalnya, kepala sekolah, teungku, guru, dosen, dan bahkan tidak serta merta melupakan tanggung jawab atas dirinya sendiri.
Ini bagian penting menurutku. Bahwa, mengutip tulisan kecil seorang 'teman dekat', "Ga harus terbang ke awan kan untuk melihat langit? Kita masih bisa melihatnya dengan tetap menapakkan kaki di tanah." bersambung ...

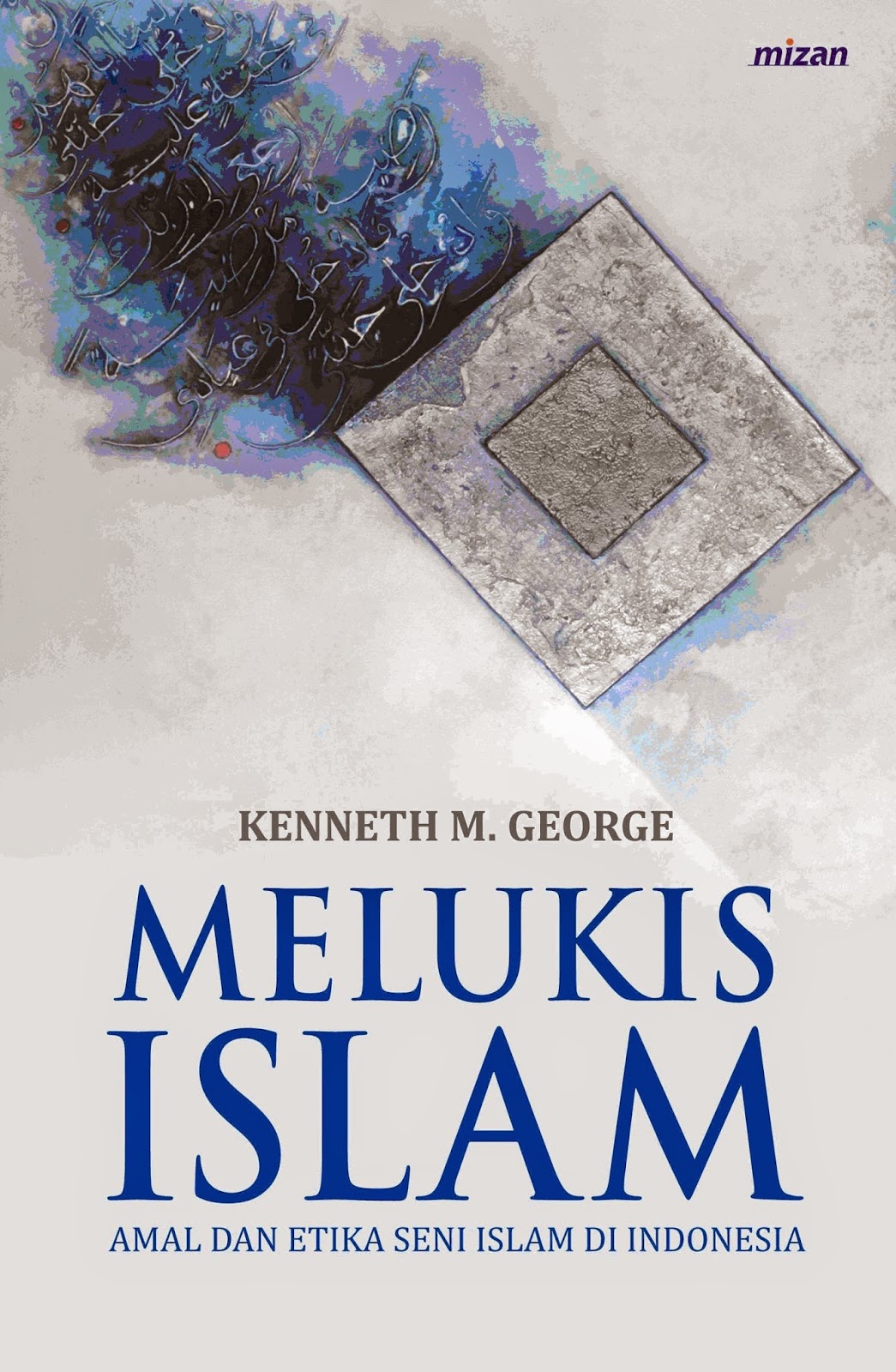
Comments
Post a Comment