Setelah Ngopi Dengan Arkeolog Indie
:deddy besi
Itu sebuah siang yang terik, kawan. Di pelataran rumah lama gaya Belanda yang telah diubah fungsi jadi warung kopi. Di bawah rindang pohon jambu, kita bertukar cerita tentang negeri kanal yang sedang kita duduki ini. Negeri yang jika ditulis riwayatnya, punya seribu satu atau bahkan lebih, cerita yang terbaca. Kita bertukar cerita, atau lebih tepatnya kau yang bercerita-aku pendengarnya, tentang abad-abad lampau. Abad-abad silam yang pernah melahirkan putra-putra terbaiknya. Yang pernah membuat tanah beserta rakyatnya penuh digdaya oleh peradaban yang mereka cipta. Kita berbicara amburadul. Tapi bukan dalam bahasan yang ngalor-ngidul.
Hingga sampai pada saat angin kencang datang, menggoyang dahan-dahan jambu di atas kepala kita, kau bercerita tentang wajah kota Venesia di kota kita. Kau jelaskan tentang kanal-kanal ukuran sekali lalu kapal, melintas saling-silang di sekujur tubuh kota. Konon, kau katakan juga, gaya tata ruang kota begitu rupa adalah hasil adopsi pekerjaan orang-orang Utsmani yang dikolaborasi dengan karya orang-orang Viet di kampungnya.
Sekejap aku terkesima. Sementara kau nikmati keterkesimaan aku dengan menyeruput kopi yang sejak sepuluh menit lewat sudah terseduh di atas meja. Lantas kau lenting juga tembakau khusus yang kau bawa dalam satu gulungan ukuran kelingking jari tangan. Dan aku masih terkesima saat lentingan tembakaumu telah terbakar menguar asap yang dalam sekejap dibawa angin. Namun, angin yang sama pula meniup-niup rambut gondrongmu itu.
Tapi aku masih mencerna, masih membayangkan tapak-tapak kanal tersisa yang jika dibayang dalam pejam mata, ia hanyalah sebentuk garis tak berpangkal-ujung, meliuk-liuk pada sekujur tanah yang telah padat oleh ramainya warung kopi, yang penuh dengan kenderaan mesin biang polusi, dan kerap dikepung oleh isu mesum terselubung.
Kubayangkan juga kapal-kapal ukuran tanggung melintas, menyisir Lampaseh, Bitai, Geuceu, Beurawe Peunayong, hingga masuk ke Daroy, merapat di sebuah anak tangga dekat Meuligoe hanya untuk mendaratkan para tamu yang lantas bersetapak menuju Masjid Raya. Dan di sana, belum juga tumbuh, apa lagi untuk sekadar berganti nama.
Sementara pengembaraan pikiranku sudah kemana-mana, kau menyambung cerita hingga sampai pada sebuah masa seorang pembesar menulis sejarah seenak kepalanya, sesuai isi perutnya. Sampai di sini, aku mengernyit dahi. Belum terlalu mengerti. Tapi itu tak lama, sebab setelahnya dengan sigap kau utarakan alasan-alasan tentang timpangnya sejarah oleh titik koma penanya.
Lantas aku jadi malas untuk membayangkan si sejarawan yang kau katakan menulis seenak perutnya itu. Yang jika hari itu juga aku ingin bertemu, bisa kutemukan wajahnya di lembar-lembar buku sejarah yang ada di banyak pustaka. Tapi bagiku, inilah hari celaka itu. Celaka oleh sebab geram dengan ketakbersisaan apa-apa dari kedigdayaan orang-orang lama.
Itu sebuah siang yang terik, kawan. Di pelataran rumah lama gaya Belanda yang telah diubah fungsi jadi warung kopi. Di bawah rindang pohon jambu, kita bertukar cerita tentang negeri kanal yang sedang kita duduki ini. Negeri yang jika ditulis riwayatnya, punya seribu satu atau bahkan lebih, cerita yang terbaca. Kita bertukar cerita, atau lebih tepatnya kau yang bercerita-aku pendengarnya, tentang abad-abad lampau. Abad-abad silam yang pernah melahirkan putra-putra terbaiknya. Yang pernah membuat tanah beserta rakyatnya penuh digdaya oleh peradaban yang mereka cipta. Kita berbicara amburadul. Tapi bukan dalam bahasan yang ngalor-ngidul.
Hingga sampai pada saat angin kencang datang, menggoyang dahan-dahan jambu di atas kepala kita, kau bercerita tentang wajah kota Venesia di kota kita. Kau jelaskan tentang kanal-kanal ukuran sekali lalu kapal, melintas saling-silang di sekujur tubuh kota. Konon, kau katakan juga, gaya tata ruang kota begitu rupa adalah hasil adopsi pekerjaan orang-orang Utsmani yang dikolaborasi dengan karya orang-orang Viet di kampungnya.
Sekejap aku terkesima. Sementara kau nikmati keterkesimaan aku dengan menyeruput kopi yang sejak sepuluh menit lewat sudah terseduh di atas meja. Lantas kau lenting juga tembakau khusus yang kau bawa dalam satu gulungan ukuran kelingking jari tangan. Dan aku masih terkesima saat lentingan tembakaumu telah terbakar menguar asap yang dalam sekejap dibawa angin. Namun, angin yang sama pula meniup-niup rambut gondrongmu itu.
Tapi aku masih mencerna, masih membayangkan tapak-tapak kanal tersisa yang jika dibayang dalam pejam mata, ia hanyalah sebentuk garis tak berpangkal-ujung, meliuk-liuk pada sekujur tanah yang telah padat oleh ramainya warung kopi, yang penuh dengan kenderaan mesin biang polusi, dan kerap dikepung oleh isu mesum terselubung.
Kubayangkan juga kapal-kapal ukuran tanggung melintas, menyisir Lampaseh, Bitai, Geuceu, Beurawe Peunayong, hingga masuk ke Daroy, merapat di sebuah anak tangga dekat Meuligoe hanya untuk mendaratkan para tamu yang lantas bersetapak menuju Masjid Raya. Dan di sana, belum juga tumbuh, apa lagi untuk sekadar berganti nama.
Sementara pengembaraan pikiranku sudah kemana-mana, kau menyambung cerita hingga sampai pada sebuah masa seorang pembesar menulis sejarah seenak kepalanya, sesuai isi perutnya. Sampai di sini, aku mengernyit dahi. Belum terlalu mengerti. Tapi itu tak lama, sebab setelahnya dengan sigap kau utarakan alasan-alasan tentang timpangnya sejarah oleh titik koma penanya.
Lantas aku jadi malas untuk membayangkan si sejarawan yang kau katakan menulis seenak perutnya itu. Yang jika hari itu juga aku ingin bertemu, bisa kutemukan wajahnya di lembar-lembar buku sejarah yang ada di banyak pustaka. Tapi bagiku, inilah hari celaka itu. Celaka oleh sebab geram dengan ketakbersisaan apa-apa dari kedigdayaan orang-orang lama.
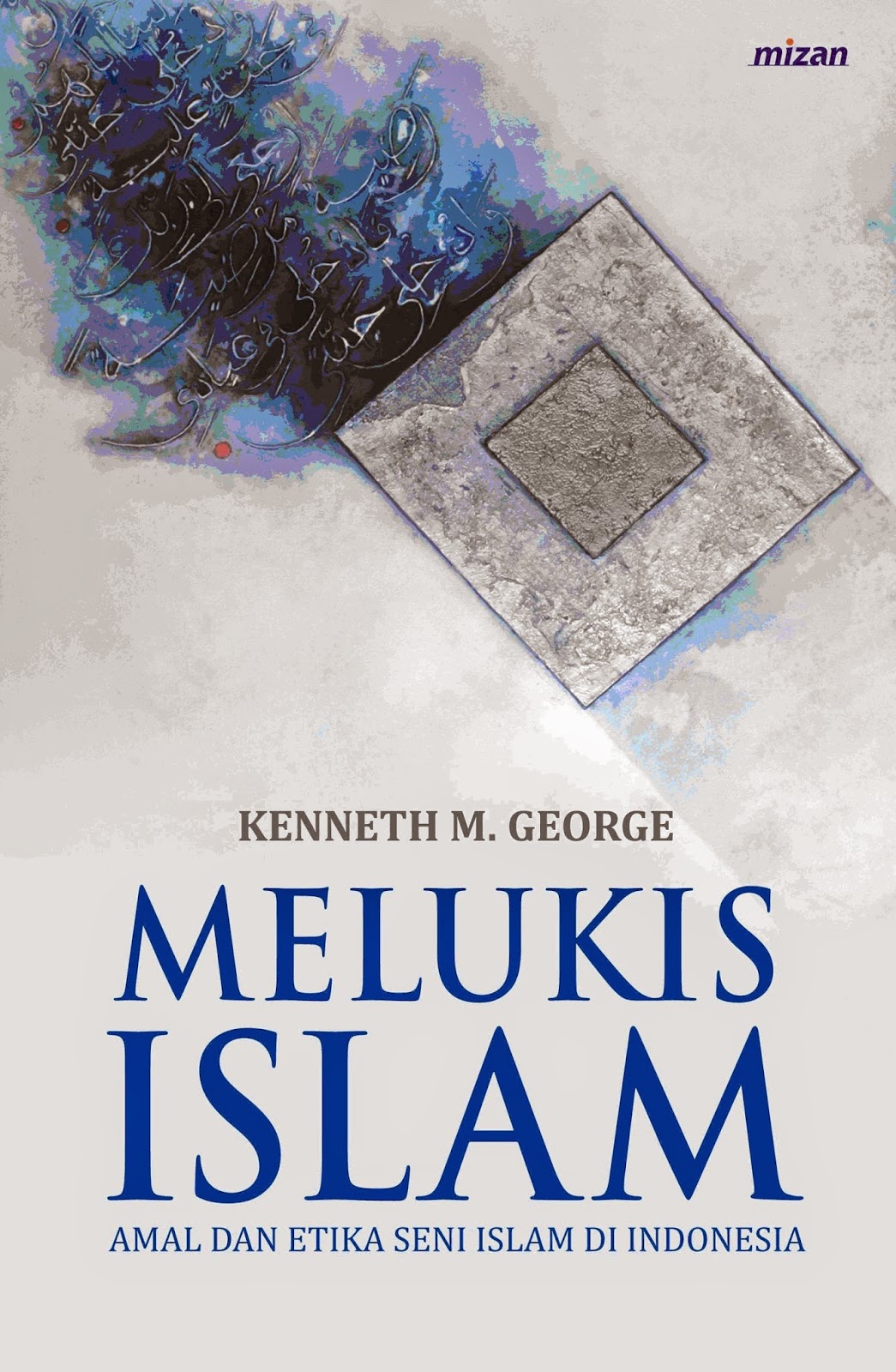
Comments
Post a Comment