Surat Balasan Buat Tuan X
SEFOLDER puisi saya kirim pada Tuan X. Via email. Zaman canggih begini rupa, kirim mengirim tulisan sudah berbentuk file. Bukan bentuk bundelan. Jadi harap maklum jika saya katakan, saya kirim sefolder puisi. Saya ulang, sefolder puisi saya kirim ke Tuan X. Tuan X seorang sastrawan. Sudah pernah mengandung dan melahirkan banyak buku.
Saya yang berkeinginan melahirkan buku, menyerahkan materi buku pada Tuan X dengan harapan dia mau membaca, lantas mau menulis sedikit saran pesan, kritik kesan, atau boleh jadi pengantar bakal buku. Sebelum, saya kirimi ia sefolder puisi, saya utarakan terlebih dahulu maksud hati saya padanya. Pengutaraan maksud hati ini, tentu saja saya lakukan dengan hati-hati mengingat asam garam yang saya kecap dalam dunia tulis menulis belumlah sampai pada jumlah bergoni-goni.
Konon lagi, perkenalan antara saya dengan Tuan X hanyalah bentuk perkenalan sepihak belaka. Maksudnya, hanya saya saja yang mengenalnya. Dia tidak. Pengutaraan maksud hati yang saya lakukan dengan hati-hati tadi adalah dengan mengirimkan surat pengantar ke alamat emailnya. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dengan sopan, saya utarakan keinginan, hingga di akhir saya menanyakan Tuan X punya kesediaan. Selesai? Belum!
Setelah beberapa hari mengirimkan surat pengantar meminta kesediaan Tuan X. Tak ada pekerjaan lain yang terpusat di pikiran selain menunggu balasan tiba. Untuk menunggu balasan surat pada zaman ini tentu saja saya harus standby di warungkopi yang ada free wi-fi. Setiap hari saya minum kopi sambil mengecek-ngecek email, barangkali ada balasan masuk. Sehari menunggu, balasan nihil. Dua hari? Belum ada juga.
Saya berpikir Tuan X pasti sibuk. Bukankah Tuan X sering diberitakan di tv dalam keadaan sibuk? Saya sabar menunggu. Tiga hari? Belum. Saya masih menunggu, sampai hari keempat saya nongkrong di warkop yang sama, beberapa pelayan di sana sudah mengenal nama saya. Bahkan, ada yang berteriak ketika saya datang: Hei, penyair. Minum apa? Kopi pancong? Saya tahu, si pelayan bukan menanyakan pesanan, tapi sedang menyindir. Tapi saya ‘tak naik pikir’ (serapan dari bahasa Aceh: han ek pikee). Toh, saya hanya kepikiran balasan dari Tuan X akan masuk dalam beberapa hari ini.
Hari kelima sejak saya kirim surat pengantar, barulah balasan dari Tuan X datang. Entah datang diantar pakai mobil atau jalan kaki, saya tak mengerti. Yang jelas, ketika saya buka email, saya lihat surat balasan sudah duduk manis di inbox surat-surat elektronik, bercampur dengan beberapa surat kaleng yang kebanyakan berisi iklan obat-obatan memperbesar kemaluan.
Agak gemetaran juga melihat surat balasan Tuan X. Ini karena saya masih anak bawang, sementara dia sudah berkedudukan disebutan ‘moyang bawang’ barangkali. Apalagi, dia itu super sibuk dan tak banyak waktu luang. Dia sastrawan nasional. Kata orang, banyak gelar yang disabetnya dari beberapa karya tulisan. Setelah menenangkan pikiran, setelah meneguk kopi pancong pesanan, setelah mengucek-ngucek mata beberapa kali, saya membuka itu surat. Surat balasan dari Tuan X. Tuan X yang baik hati. Tuan X yang begitu peduli.
Hati-hati saya membaca. Tak ingin melewatkan titik koma, apalagi tertinggal beberapa kata. Tapi. Astaga! Saya membaca:
“Terima kasih telah memercayakan saya sebagai orang pertama yang akan membaca karya Anda. Salam kenal kembali. Semoga Anda sehat-sehat saja. Di surat yang saya baca, karya Anda berbentuk puisi. Benarkah? Hmmmm… Saya sangat terkesan dengan anda hari ini.
Tapi, sebelum saya mengungkapkan kesediaan saya untuk membaca dan mengulas karya Anda, satu –dua dst.- pertanyaan yang timbul dalam benak saya kepada Anda. Anda tahu apa itu sastra? Anda tahu apa itu puisi? Kapasitas apa Anda berani menulis puisi?”
Tak saya teruskan membaca surat balasan. Cukup sampai di tiga pertanyaan. Ini sudah cukup mengganti keadaan. Dari pertama gemetar, sekarang sudah bertambah menjadi gemetaran. Gila. Saya seruput lagi kopi. Saya menenangkan diri. Sebab, tak saya bayangkan sebelumnya akan menerima balasan begini rupa. Ini di luar akal sehat saya.
Akal saya masih baik-baik saja. Tidak berpenyakit akut. Panu pun nggak. Saya berpikir, masih adakah orang begini rupa setelah tsunami? Atau ini adalah sisa satu-satunya, untuk dijadikan contoh barang bagi siapa saja yang mau bertaubat pada-Nya? Ah, sudahlah. Kenapa harus saya indahkan ini balasan dengan pikiran macam-macam.
Jika Tuan X sudah bertanya, kenapa tak kujawab saja. Maka, kujawab dengan segera balasan surat Tuan X, begini:
“Tuan X yang terhormat. Terima kasih telah membalas surat saya. Saya cukup mengerti dengan pertanyaan yang Tuan lemparkan ke hadapan jidat saya. Untuk ini, sudilah kiranya saya menjawab sebagaimana akal saya bekerja.
Tuan, terus terang saya tak seberapa tahu apa itu yang disebut dengan sastra. Baik secara etimologi maupun terminologi. Saya tak belajar teori sama sekali. Yang jelas saya suka baca buku sastra. Itu saja. Dan dari bacaan-bacaan yang pernah saya baca, pun saya sedikit memahami sesuai kerja otak saya apa yang dimaksud dengan sastra, dengan sengaja saya tidak akan mengungkapkan itu kepada Tuan. Sebab saya tahu, itu sudah barang tentu jauh dari kebenaran menurut Tuan nanti.
Bersoal puisi. Saya langsung melompat ke soalan tentang apa kapasitas saya menulis puisi. Begini Tuan yang budiman. Bagi saya puisi bukanlah milik segelintir orang yang hanya boleh dibaca dan ditulis oleh orang-orang tertentu saja. Atau dengan kata lain, sebutlah bahwa untuk menulis puisi mesti mewarisi darah ‘biru’ kepenyairan atau apalah namanya. Puisi, bagi saya, tentu tidak sama dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan keyakinan atau peribadatan seseorang.
Hingga jikalau salah dalam menulisnya akan menyesatkan banyak orang, dan pada tahap akhir, penulis beserta segenap pembacanya akan dijebloskan ke dalam penjara panas di akhirat sana. Saya pernah menulis puisi di dalam jamban. Sambil berak malah. Tapi setelah menerima surat balasan Tuan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot itu, saya jadi membayangkan proses kreatif Tuan hingga menghasilkan tulisan-tulisan bermutu walau pun bertema selangkangan.
Saya membayangkan, sebelum menulis pasti terlebih dahulu Tuan mengambil wudhu’, salat sunat dua rakaat, membaca beberapa doa, baca mantra, bakar kemenyan atau malah sebelumnya mandi kembang segala. Hmmm… Seribet inikah menulis puisi? Jika begitu saya berhenti hari ini. Oya, tentang keinginan saya, lupakan saja. Terima kasih.”
Setelah menjawab pertanyaan Tuan X, entah kenapa hati saya begitu lega. Serasa lapang dalam dada. Kepala saya seperti dipenuhi banyak diksi yang layak ditoreh dalam bait puisi. Saya tulis satu puisi. Tuan X yang baik hati. Bagimu puisi itu sakral. Bagi saya tidak. Tuan harus ingat itu. Puisi tidak sakral. Titik!
Banda Aceh, Juni 2012.
[repost. sebelumnya telah dimuat di Acehpost.com]
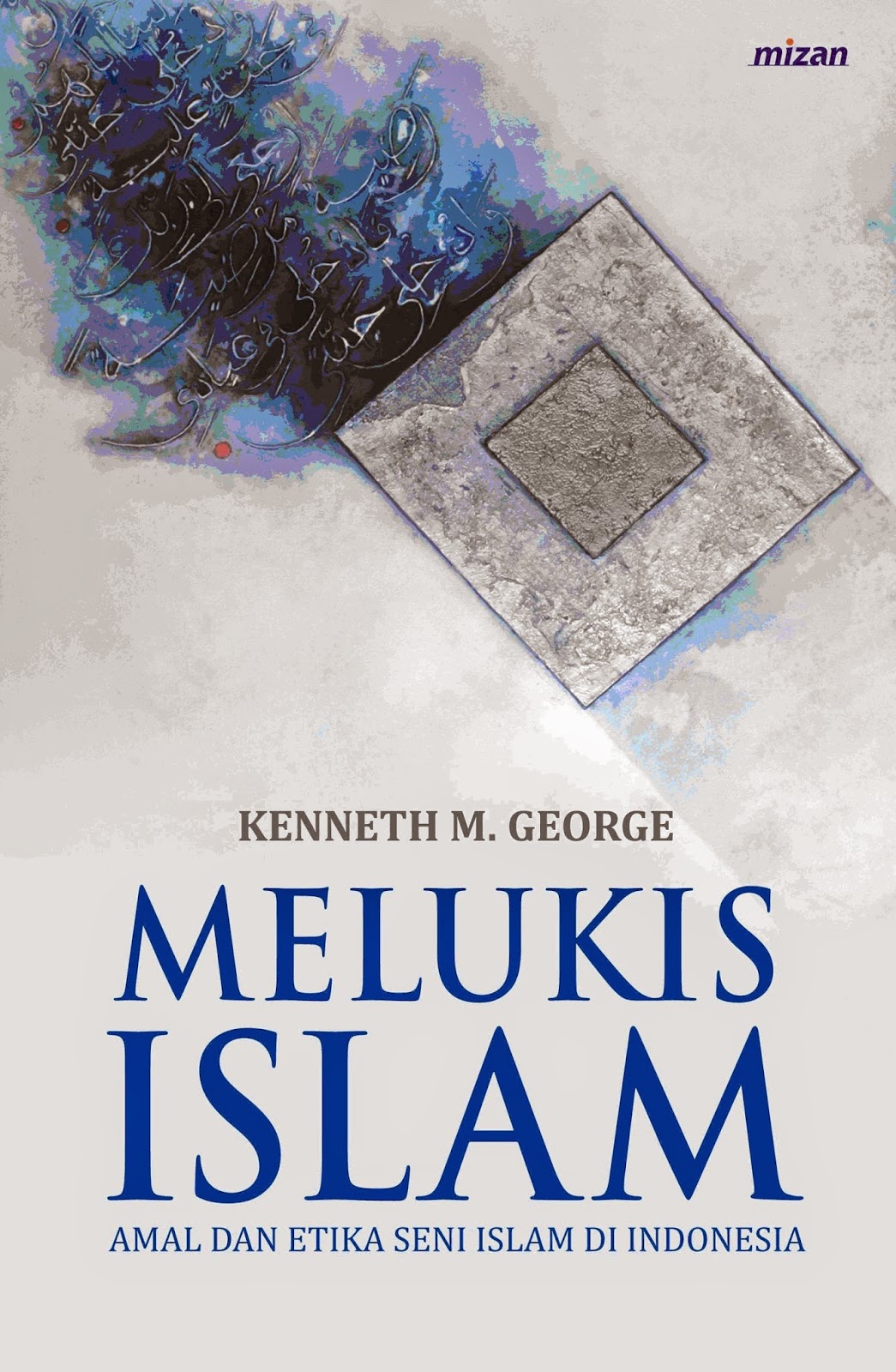
Comments
Post a Comment