Ketika Lagu-lagu Protes Mulai Dinyanyikan
Dalam diskusi bertajuk Musik Aspirasi
Sakti di Kemang Jakarta Selatan 24 April 2014 lalu, Sawung Jabo, musisi senior
Indonesia, berujar "Apalah gunanya berkesenian kalau enggak sesuai dengan
kenyataannya.” Menurutnya, Indonesia adalah negara bebas beropini, dan penyanyi
enggak usah takut-takut mengangkat tema sosial dalam berkesenian.
Maka sebagai apresiasi terhadap
beberapa penyanyi atau band yang ada di Aceh yang mengangkat tema sosial dalam berkeseniannya,
tulisan ini hadir sekadar untuk menggenapi tulisan Muhajir Abdul Aziz dalam
rubrik Apresiasi berjudul Seungkak Malam Seulanyan, Minggu, 27 April 2014 lalu.
Muhajir benar, “Melawan membutuhkan lagu. Aceh adalah tempat di mana
perlawanan pernah dilakukan sekaligus lagu-lagu tentang itu dinyanyikan.”
Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa lagu, syair, atau hikayat adalah ‘viagra’
bagi sebuah perlawanan.
Tapi sudah barang
tentu isi lagu, syair, atau hikayatnya itu harus bertema tentang perlawanan
pula. Sebab adalah mustahil ketika genderang perang perlawanan ditabuh, lirik
serupa “Meuheut hate nyoe jak saweu dinda. Peukeuh gata mantoeng sidroe.
Peukeuh adoe mantong setia. Oh.....Dek Safira,” dinyanyikan massal dengan
maksud menaikkan semangat perlawanan. Ini jelas-jelas tak mungkin, tentu saja.
Pertanyaannya, Aceh
sudah sejak 2005 damai, tapi kenapa masih ada perlawanan? Di sinilah uniknya
ini daerah yang berjuluk Serambi Mekkah. Perlawanan tak pernah berhenti ketika
ketidakadilan dan segenap keluarganya masih merajalela dalam kehidupan
masyarakat. Dan orang Aceh, barangkali, sudah dari sononya begini. Selalu
ambil bagian untuk melawan.
Jika semasa konflik,
perlawanan bersenjata terasa gencar dilakukan dengan musuh utama adalah
ketidakadilan Jakarta (Pemerintah Pusat). Musuh perlawanan sekarang lain lagi.
Sebab setelah damai 2005 hingga sekarang, laku politik, fakta bahwa masyarakat
belum merasakan keadilan, kesejahteraan jauh di depan mata, dan tindak
kekerasan masih kerap terjadi adalah bukti Aceh belum bisa berdamai dengan
dirinya sendiri. Dan untuk memperoleh kedamaian ini, sebagaimana pengalaman
yang sudah-sudah, perlawanan tetap harus dilakukan.
Bedanya, kalau
perlawanan dengan Jakarta dilakukan dengan naik gunung dan angkat senjata,
perlawanan atas ketimpangan sosial sekarang dilakukan dengan media lain. Seni
musik salah satu alternatifnya. Lirik-lirik lagu Seungkak Malam
Seulanyan, sebagaimana telah diulas Muhajir sebelumnya adalah bentuk perlawanan
melalui seni yang di maksud.
Tapi Seungkak Malam
Seulanyan tidak sendirian dalam aksi ini. Pasalnya, kelompok musik bernama
Amroe & Pane Band, sebuah band indie yang setahun sebelumnya telah
mengeluarkan album berjudul Eh Malam Gam, juga turut ambil bagian dalam
melawan. Lagu berjudul Piyoh Pajoh Peng Kamoe (P3K), yang telah
dinyanyikan dalam berbagai acara seni di Banda Aceh dan telah diunggah dalam
laman youtube, adalah perihal kenapa band ini harus masuk dalam lingkungan
musik perlawanan di Aceh masa sekarang.
Dalam lagu ini, Amroe & Pane
Band menyosor orang-orang yang gila uang dan gila kuasa paska damai sebagai
musuh utama. Di mana bagi orang-orang yang untuk meraih dua hal itu, tindak
korupsi menjadi pekerjaan wajib dan dianggap lumrah belaka. Tapi Amroe &
Pane Band cukup mengerti bahwa korupsi dan tukang korup (koruptor) adalah
sebenar-benarnya penyakit masyarakat. Yang derajat penyakitnya mungkin (atau
jelas-jelas) dua, tiga tingkat di atas keberadaan kupu-kupu malam di Banda Aceh, yang
sekarang harus berusaha lebih keras dan bekerja lebih lihai lagi untuk
mengukuhkan eksistensinya oleh sebab WH terus menguntit keberadaan mereka.
Untuk melawan penyakit korupsi
dan keberadaan koruptor sebagai sampah masyarakat, Amroe & Pane Band tak
tanggung-tanggung. Lirik ekspresif mereka cipta dan nyanyikan. Penggalan
liriknya bisa di baca: “Pike, peu kapike nyoe nanggroe Ma kah, hase nanggroe
ka kuran keu droe. Peu kapike nyoe nanggroe Yah kah. Pike, peu kapike nanggroe Nek
Tu kah, kamat nanggroe galak-galak kah. Peu kapike nyoe nanggroe Biek kah. Piyoh,
hai tikoh pajoh peng.”
Menghadapi pelbagai
penyakit sosial, lagu-lagu Amroe & Pane Band, juga lelagu Seungkak Malam
Seulanyan, dengan lirik-lirik protes, kritis,
dan melawan seperti itu adalah bagian terkecil dari sebuah perlawanan
bermediakan seni. Di sini, dua band indie itu telah dan (semoga) terus
melakukannya dengan media seni musik sebagai senjata.
Dan jika gaung
lagu-lagu perlawanan itu tersebar secara masif, bisa dibayangkan bagaimana
tidak nyamannya para begundal (biang ketimpangan sosial) hidup di Aceh. Bisa
dibayangkan pula, bagaimana malunya seorang koruptor yang pada sebuah acara makan malam
keluarga, seorang anaknya secara spontan bernyanyi, “Pike, peu kapike
nyoe nanggroe Ma kah, hase nanggroe ka kuran keu droe. ...
Piyoh, hai tikoh pajoh peng.”
Atau jika ingin ditambah lagi
ilustrasi dari efek lagu-lagu perlawanan itu apabila serentak dinyanyikan.
Bayangkan sendiri, bagaimana letoy-nya seorang panglima yang kemaruk
uang ketika dihadapkan dengan lirik lagu Amroe & Pane Band lain berjudul Peng
Griek:
Rakyat lon teungoh mumang. Bak peutimang, heut dum panglima prang.
Beutoi seujarah peugah. Gara-gara peng griek, ditiek pejuang. Beutoi Abua
peugah. Gara-gara peng griek, panglima meu prang.Panglima teu khem seunang. Bak
kursi leupon, punggong nyan han leukang. Panglima meu seunang-seunang. Rakyat
ka dikliek, hanso na peuteunang.[]
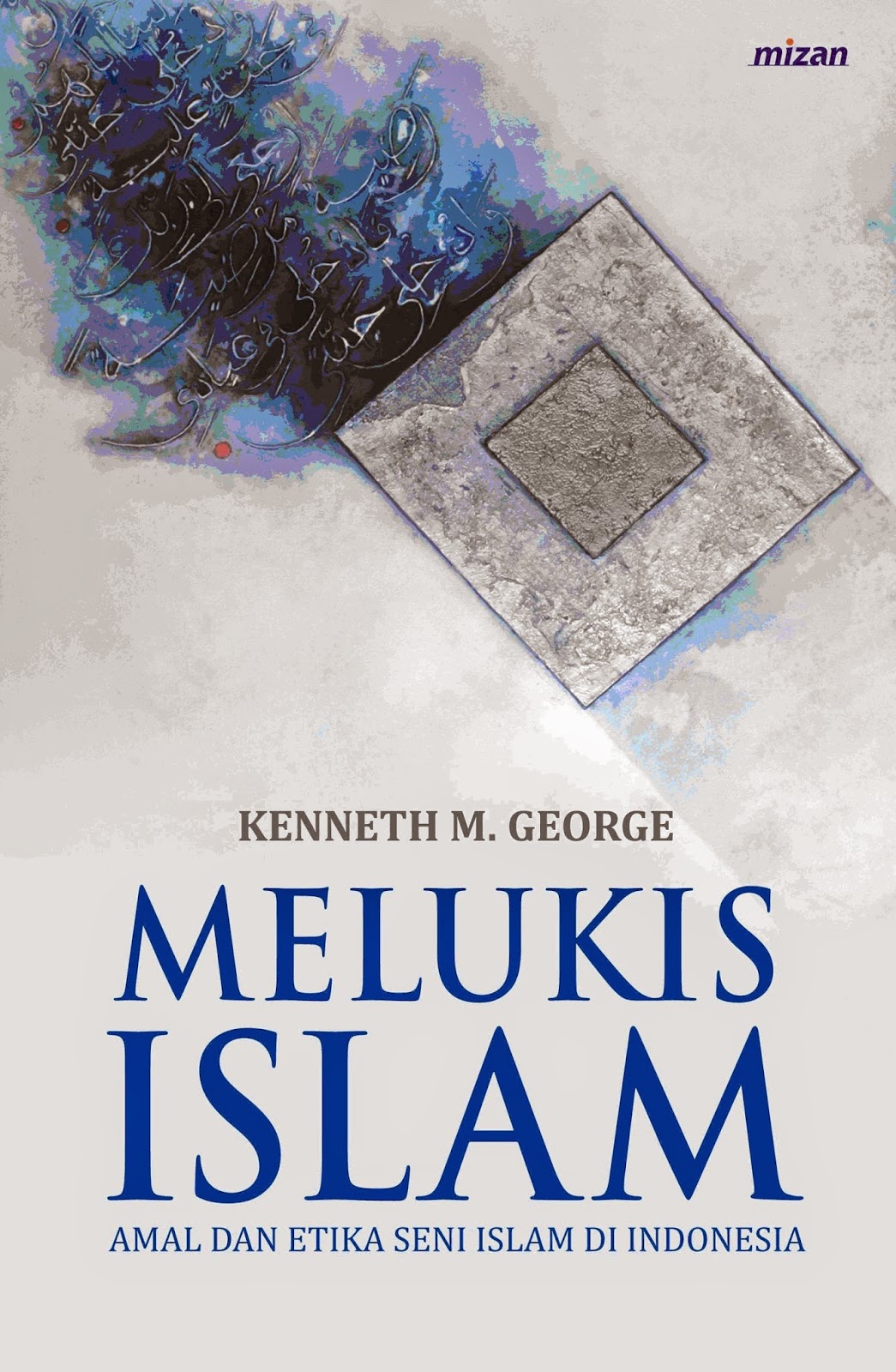
Comments
Post a Comment